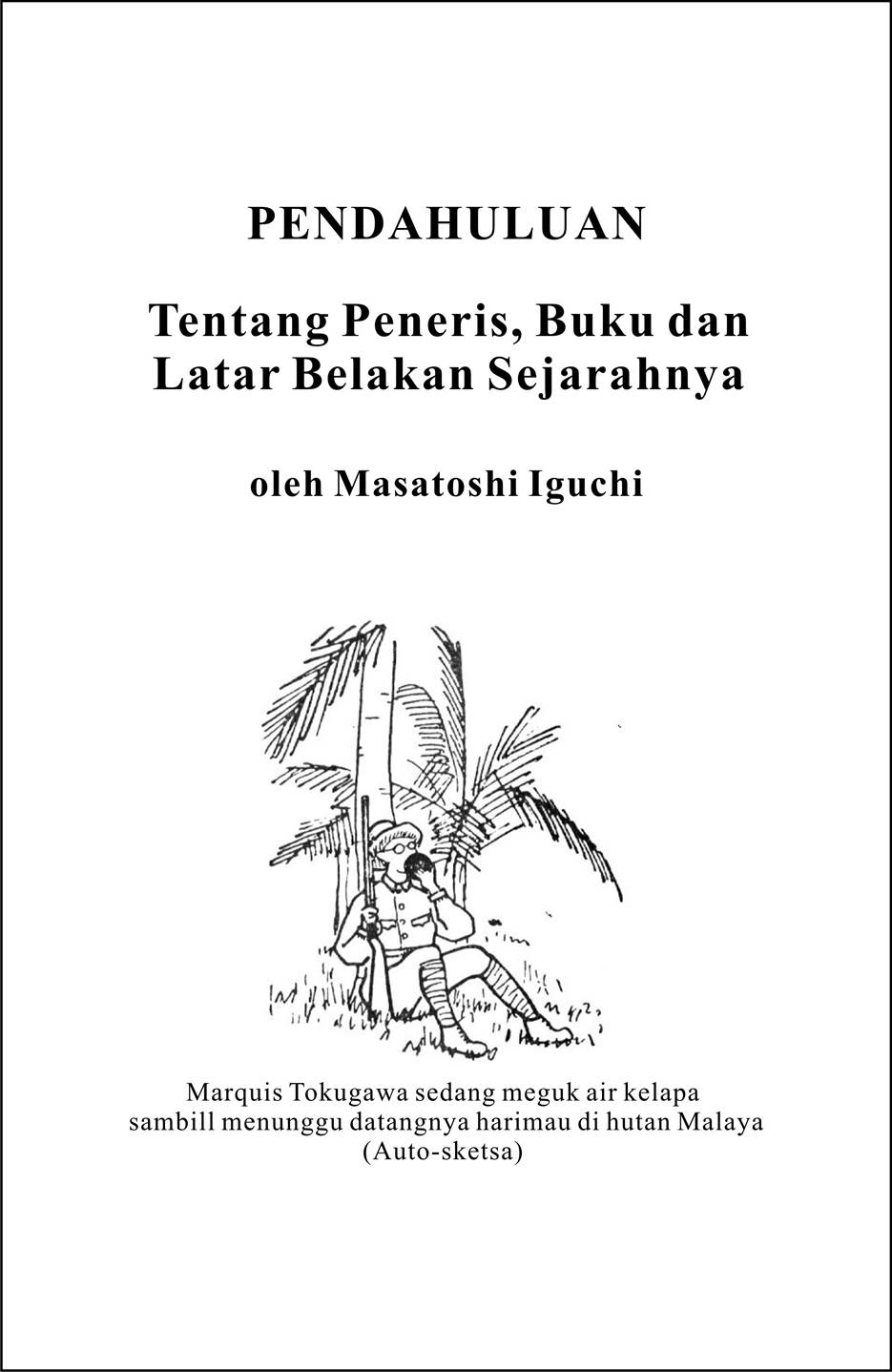Illustration in the front page from:
Yoshichika Tokugawa, Jagatara-kikau, Kyōdo-kenkyu-sha, Nagoya 1931
Tentang Peneris, Buku dan Latar Belakang Sejarahnya
Dilihat dari buku ini kita dapat mengetahui bahwa penulis adalah seorang tokoh panutan. Ia merupakan generasi ke-19 dari Owari-Tokugawa, keturunan keluarga Tokugawa[1] yang mendirikan Shogun di awal abad ketujuhbelas dan menguasai Jepang selama hampir tiga abad sampai Restorasi Meiji (1868). Berikut ini adalah profil ringkas yang diberikan oleh Tuan Yoshinobu Tokugawa, cucu laki-laki penulis.
Yoshichika (nama kecil, Kinnojō) lahir pada tanggal 5 Oktober 1886 adalah putra kelima Pangeran Yoshinaga Matsudaira dari Echizen. Pada tahun 1908, ia berhasil menjadi tokoh panutan dan menjaga keutuhan Owari-Tokugawa. Pada tahun 1909, ia menikahi putri leluhurnya bernama Yoneko. Sebagai seorang bangsawan dengan latar belakang prajurit, ia memiliki karir yang luar biasa. Ketika hampir semua dari ahli waris menjadi politikus, diplomat atau pegawai, ia mempelajari sejarah dan ilmu biologi di Tokyo Imperial University dan melanjutkan studinya di Institut Penelitian Biologi Tokugawa (The Tokugawa Institute for Biological Research) dan Institut Sejarah Ilmu Kehutanan Tokugawa (The Tokugawa Institute for the History of Forestry) yang ia dirikan sendiri pada tahun 1918 dan 1923. Laboratorium ini bukanlah tempat untuk orang kaya tetapi merupakan institusi riset tingkat tinggi. Sebagai seorang direktur, ia merekrut Prof. Hirotaro Hattori, seorang ahli ilmu biologi yang terkenal dan juga merupakan gurunya di universitas. Pada tahun 1931, ia juga mendirikan sebuah museum seni yang diberi nama Museum Seni Tokugawa (The Tokugawa Art Museum) yang dibuka untuk masyarakat umum dan sebagian harta benda warisan keluarganya diberikan dan disimpan di museum tersebut. Kemudian ia menggabungkan museum seni dan laboratorium miliknya dalam Yayasan Tokugawa Reimeikai (The Tokugawa Reimeikai Foundation)[2] yang didirikan pada tahun yang sama.
Tidak seperti ilmuwan pada umumnya, penulis sangat gemar berburu binatang buas, bukan burung dan rubah yang ia buru tetapi beruang, harimau dan gajah, dan karena kegemarannya[3] inilah ia dapat mengenal Soeltan Johor. Pada Tahun 192, ia memilih Malaya sebagai pengganti Hawaii untuk melakukan pergantian udara yang bermanfaat bagi kesehatannya dan dalam perjalanannya itulah ia mampir ke pulau Djawa untuk pertama kalinya. Pada tahun yang sama, ia pergi ke Eropa dengan isterinya dan menetap selama satu tahun. Ia kembali mengunjungi pulau Djawa untuk kedua kalinya pada tahun 1929 sebagai delegasi dari Jepang pada acara Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat (The Fourth Pacific Science Congress) yang diselenggarakan di Batavia-Bandoeng. Dalam perjalanannya kembali ke Jepang, ia memperluas perjalanannya ke Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi) dan Malaya. Menurut cucu laki-lakinya, perjalanan ini merupakan ‘Perjalanan seorang Pangeran’ dan sungguh mengejutkan bahwa pada saat-saat yang memungkinkan ia berperilaku seperti rakyat biasa. Sebagai contoh, pada saat sendirian di Singapoera, ia tinggal di hotel murah dan makan di restoran pinggir jalan. Di hutan Malaya, ia berkemah bersama-sama penduduk setempat dan makan apapun yang disajikan. Ia belajar bahasa Melayu sendiri tanpa didampingi oleh seorang penterjemah dan kemudian menjadi pengarang buku “Bahasa Melayu dalam Ampat Minggu” (Yoshichika Tokugawa, Sumitaka Asakura, Bahasa Melayu dalam Ampat Minggu, Daigaku-Shorin, Tokyo 1937).
Marquis Tokugawa adalah seorang penganut faham liberalis menyebut dirinya sebagai ‘Raja Terakhir’. Sebagai orang yang tinggal di Istana Raja, ia mengejutkan masyarakat Jepang dengan usulan “penghapusan sistem panutan” lama sebelum dipaksa oleh Amerika setelah perang dunia kedua. Ia memberikan tanah warisannya di Nagoya kepada penguasa kota di awal tahun 1931.
Ia juga seorang relawan. Ketika perang dunia kedua terjadi di wilayah Pasifik pada bulan Desember 1941, ia langsung menawarkan diri sebagai sukarelawan dan terbang ke Singapoera. Di sana ia tidak bekerja pada angkatan perang tetapi sebagai Penasehat Konsulat Tertinggi untuk angkatan perang. Ia menggunakan kekuasaan penuh dari kekaisarannya, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Panglima, untuk menyelamatkan para Soeltan dan orang pribumi serta teman-teman akademisnya. Salah satu teman akademisnya yang diselamatkan adalah Dr. R. E. Holttum yang juga Direktur Kebun Botani, dan juga orang yang bersama-sama pergi ke pulau Djawa untuk mengikuti acara Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat duabelas tahun yang lalu. Ia melindungi Museum Raffles dengan sempurna dan membiarkan aktivitas riset tetap berjalan, bersama-sama dengan ilmuwan Jepang dan Staf Britania, yang belakangan dibebaskan dari hukuman penjara atas perintahnya. Ia juga mengorganisir suatu pertemuan ilmuwan Jepang yang diutus untuk menempati wilayah masing-masing dan mengkoordinir aktivitas mereka. Selama menetap di Singapoera, ia membiayai sendiri kunjungannya yang ketiga ke pulau Djawa tetapi ia tidak memiliki hasrat untuk menulis suatu karangan.
Meskipun banyak berjasa, Marquis Tokugawa dilarang berbicara di depan para buruh untuk beberapa lama setelah Perang Dunia Kedua, karena ia sedang diadili di Pengadilan Mac Arthur Tokyo dengan tuduhan bekerjasama dengan rejim militer.
Setelah Perang Dunia Kedua, ia mendukung pembentukan Partai Sosialis dan menjadi pimpinan partai tersebut, namun pada pemilihan Walikota Nagoya, di kota asalnya, ia kalah oleh Partai Konservatif akibat persiapan yang tidak cukup. Selanjutnya ia menjadi pemimpin beberapa sekolah dan pimpinan perusahaan. Ia senang berburu binatang buas dan dapat membedakan mana binatang berbahaya dan tidak oleh karena itu ia menjadi pemimpin sebuah perlindungan cagar alam. Ia mempunyai perhatian khusus terhadap kesejahteraan orang-orang cacat jasmani dan memberikan sumbangan kepada mereka untuk jangka waktu panjang. Cucu laki-lakinya selalu ingat pada motivasinya yaitu untuk orang lain, baik yang ia jumpai di kereta atau siapapun yaitu negara, manusia, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan keluarga. Ia meninggal 6 September 1976 pada usia 89 tahun 11 bulan.
Pada kata pengantar didalam buku koleksinya, “Journeys to Djakarta” yang terbit tahun 1931, Marquis Tokugawa menjelaskan bahwa tujuan penerbitannya adalah agar masyarakat mengenal Nanyo (= c. nanyang. Menurut literatur, Nanyo adalah samudra selatan, sekarang Asia Tenggara), ketika kaum imperalis dan kapitalis Jepang sedang melebarkan sayap mereka dari Timur Jauh, dan menggemakan pentingnya Asia Tenggara. Ia menyayangkan fakta bahwa aktivitas relawan Jepang di wilayah itu menurun sehingga jumlah penduduk Jepang berkurang. Menurutnya hal tersebut terjadi akibat peraturan dari penguasa wilayah itu[4]. Ia mendesak anak muda pada saat itu untuk mengingatkan pedagang bebas dan buruh upahan yang aktif pada abad 16 dan 17 sebelum negeri ditutup[5]. Ironisnya itu terjadi pada pemerintahan Shogun, nenek moyangnya sendiri. Ia juga mengingatkan hal itu kepada orang-orang terhormat yang pernah dijumpainya di pulau Djawa dan Malaya, dan berharap agar masyarakat umum memandang Nanyo tanpa prasangka[6].
Sebenarnya, artikelnya merupakan laporan perjalanan sederhana yang ditulis seperti buku harian dengan menggunakan gaya bahasa Jepang[7], dan ia menguraikan dengan terus terang dan lucu, apa yang ia lihat, dengar dan pikir sebaik mungkin. Pengamatannya mendalam dan tajam, membuktikan bahwa apa diperoleh hanya melalui transparansi dan refleksi dari seorang ilmuwan dan sejarawan. Tidak hanya dijelaskan dalam bahasa ilmiah, seperti bagaimana tumbuhan dan binatang hidup di pulau Krakatau yang binasa oleh letusan gunung berapi, tetapi juga keterangan tentang peninggalan Kerajaan Hindu yang tersisa di candi Prambanan dan sejarah dari reruntuhan Istana Air Soeltan, atau dari topik yang bervariasi. Pandangan uniknya adalah dalam menggambarkan candi Boroboedoer, “monumen Buda itu terlihat sangat berharga, ketika aku memikirkan waktu dan usaha yang disumbangkan untuk pemugaran”. Laporannya sangat rinci, sehingga pembaca yang tidak sabar mungkin merasa sangat berlebihan, tetapi boleh jadi karena ia adalah seorang yang perfeksionis yang tidak akan mempersingkat atau merubah fakta yang ia peroleh dan akan mengungkapkan semuanya melalui pena. Beberapa foto diambilnya sendiri - sebuah hobi yang mewah bagi pelancong pada saat itu - disisipkan pada setiap teks bacaan.
Yang sangat mengagumkan adalah bagaimana ia memperoleh banyak pengetahuan dalam periode perjalanan yang singkat, diluar tingkatan buku penuntun, sekalipun ia memiliki kelebihan sebagai tokoh panutan tertinggi yang memungkinkan ia untuk mengunjungi bagian dalam istana dan berbicara secara langsung kepada para raja dan bangsawan[8]. Ia sangat berbudaya dengan latar belakang Timur dan Barat yang menjelma dalam dirinya dari sejarah dan literatur seperti kiasan dan metafora yang banyak dijumpai dalam komposisinya serta terminologi biologi dari perbendaharaan akademisnya. Ia senang dengan pemakaian ungkapan dan idiom dalam bahasa Cina asli, dimana hal tersebut merupakan kebiasaan umum setelah kebijakan “penyederhanaan bahasa nasional” yang mengacu pada pengaruh Amerika pasca perang.
Agak terlihat ganjil jika disampaikan kepada pembaca bahwa tidak ada orang pribumi yang nampak pada Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat, yang pada kenyataannya tercatat beberapa nama orang pribumi diantara anggota dari orang-orang Belanda di Hindia Timur (Belanda di Indonesia). Apakah itu termasuk keluhan orang Indonesia karena orang-orang Belanda tidak memberikan pendidikan kepada orang pribumi[9]? Menurut seseorang, pada saat itu hanya beberapa orang saja bisa ambil bagian dalam ilmu pengetahuan, bahkan di negara-negara maju. Selain itu hanya ada sekitar selusin institusi pendidikan tertinggi ada diseluruh Kerajaan Belanda termasuk tiga sekolah tinggi yang ada di pulau Djawa[10]. Selain argumentasi ini, orang boleh berasumsi bahwa pegawai Kebun Botani Buitenzorg (Bogor) dan asisten di Kebun Botani di dataran tinggi Tjibodas adalah penduduk asli yang menerima fasilitas dan tradisi riset setelah kemerdekaan, atau pengusiran orang Eropa pada tahun 1950. Kenyataannya, pegawai muda dari Landbouw Hoogeschool dan Nederlandsch Indische Veeartsen-School, dan Technische Hoogeshool te Bandoeng dapat menjadi profesor di dua institusi sekaligus di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Bandoeng (ITB).
Dari semua tulisannya selama di pulau Djawa, Marquis Tokugawa tidak membuat komentar apapun baik tentang politik atau orang-orang Belanda yang mengatur Hindia Timur. Saat kunjungan pertamanya pada tahun 1921, ia sangat memuji meriam tua di Batavia tua. Pemikiran tentang kepastian kemerdekaan pulau Djawa menyebabkan meriam itu banyak dikunjungi para peziarah dan “mengesampingkan perihal kemerdekaan untuk sementara waktu.” Ia juga menceritakan dengan lucu, saat mendiskusikan tengkorak seorang pengkhianat abad ke-18, Pieter Erbervelt, “Sangatlah menakutkan melihat sebuah kepala dibiarkan menjadi tengkorak, jika seseorang mengkhianati orang-orang Belanda.” Pada perjalanannya yang kedua tahun 1929, ia tidak menyebutkan segala sesuatu mengenai tanda-tanda perubahan yang akan menjadi kenyataan pada generasi berikutnya. Di pulau Djawa, ia mendengar pertumbuhan aktivitas kaum nasionalis dan komunis[11]. Di Manchuria[12], anggota militer negaranya sedang memperhebat pergerakan mereka. Apakah ia tidak peduli akan berbagai hal itu? Tentu saja tidak, sebab ia telah melihat keduanya, Asia yang miskin dan Eropa yang makmur dan menyadari kekejaman dari penguasa kolonial. Sesungguhnya, ia menunjukkan simpati kepada ajudan Soeltan Johor yang menentang kekerasan orang-orang Inggris yang mengendalikan Malaya (bagian dari perjalanan ini tidak termasuk dalam terjemahan ini). Kita mengetahui bahwa bagaimanapun seluruh dunia menyambut pemulihan perdamaian, dan hubungan internasional di Asia menjadi tenang setelah Perang Dunia Pertama.
Mungkin penggemar bacaan seperti Marquis Tokugawa ini sudah membaca sebuah buku yang ditulis oleh penyelidik alami, Alfred Russell Wallace, dan berbagi pandangan yang sama tentang masa lalu. Di dalam bukunya yang terkenal, “The Malay Archipelago” yang diterbitkan tahun 1869, Wallace menulis, “Aku percaya bahwa sistem orang-orang Belanda adalah yang terbaik untuk ditiru, ketika bangsa Eropa menaklukkan atau memperoleh pemilikan dari negeri yang dihuni oleh orang-orang yang rajin tetapi semi-barbar”. Wallace setuju dengan pendapat J. W. B. Money yang terdapat pada buku “Java or How to Manage a Colony” yang terbit tahun 1861 dan memprotes pendapat Multatauli “Max Havelaar or The Coffee Auctions of the Dutch Trading Company yang terbit tahun 1860 sebagai “cerita yang sangat panjang juga membosankan dan menyimpang dari pokok pembicaraan.” Ada pendapat bahwa uang menentukan sistem kebudayaan, dengan kata lain, uang terkenal dapat mengubah paksa sistem kultur. Salah satu tulisannya, “Pribumi kelas bawah gembira dan bahagia, dan yang paling kaya pernah saya lihat dibanyak negeri manapun kecuali Amerika Utara.” Seorang ahli sejarah pulau Djawa, Donald M. Campbell menyimpulkan, “Ketika semua dikatakan dan dilaksanakan, kenyataannya, sistem kebudayaan melakukan sesuatu yang tak terukur jumlahnya untuk pulau Djawa” (Campbell, D. M., Java:Past and Present, Vol. I, William Heinemann, London 1915).
Cerita tentang pulau Djawa sebagai sebuah pulau yang kaya sudah tentu benar untuk beberapa abad, seperti kata orang-orang Cina pada tahun 1172-78 dalam buku, “Menjawab Pertanyaan tentang Bagian Luar Puncak Gunung” (Answers to Questions about the Exterior of Mountain Peaks, 嶺外代答) bahwa “Kediri (pulau Djawa) dan Sriwijaya (Sumatra) adalah negara-negara makmur dan kaya setelah Tajik (Saracen): mereka juga mengatakan dalam bukunya “Catatan Ringkas di Pulau Asing” (Consice Notes on Foreign Islands, 島夷志略) bahwa “Di abad keempat belas daratan yang paling luas dan paling padat penduduknya adalah di Samudra Timur”. Ladang yang subur dan datar, dengan produktivitas berasnya dua kali lebih besar dari yang lain. Orang-orang di sana tidak pernah mencuri dan tidak pernah mengambil apapun yang jatuh di jalan. Itulah kenapa disebut “pulau Djawa yang tenang” (Pacific Java). (H. Wada, A History of Races in The South-East Asia (a text book for University of Air), 1987).
Ketika Marquis Tokugawa berkunjung, pulau Djawa masih merupakan negeri yang tenang dan kaya, hubungan antar penduduk pribumi dan orang asing juga tampak bersahabat, seperti pujian Frank G. Carpenter (1926)[13] dan John C. van Dyke (1929)[14], yang keduanya berkunjung ke sana dari Amerika.
Komentar ini mungkin agak berlawanan dengan Generasi setelah Perang Dunia Kedua (Post-Second-World-War), tidak hanya dari negara-negara bekas jajahan tetapi juga dari negara-negara penjajah. Di sekolah mereka diajarkan seolah-olah kolonialisme dalam bentuk apapun tetap salah dan orang-orang terjajah itu selalu menderita. Beberapa sejarawan juga mengatakan hal yang sama bahwa orang-orang Belanda telah memanfaatkan segalanya sebelum Indonesia menjadi negeri yang merdeka, dengan kontribusi yang sedikit sekali untuk pengembangan negeri itu. Apakah mereka dengan sengaja atau tidak melalaikan fakta itu? Bahwa kekayaan Hindia Timur, seperti bijih sumber alam dan kekayaan fosil menjadi penting, selain itu produk pertanian yang dapat diperbaharui setiap tahun, tidak seperti emas dan perak dari Aztecs dan Incas yang telah direnggut oleh Penakluk dari Spanyol (Conquistadors Spanyol). Bagi orang-orang Belanda, pulau Djawa sebagai bagian dari Hindia Timur, bukan semata-mata daerah jajahan ekonomi lagi[15] setelah akhir abad ke 19. Hal itu terjadi ketika Terusan Suez dibuka dan perjalanan lebih dari sepuluh ribu mil dari Belanda menjadi lebih mudah dan aman serta lebih banyak wanita menetap di sana untuk mengembangkan pulau Djawa[16]. Mereka menginvestasikan jumlah yang sangat besar untuk infrastruktur dan pada waktu itu pulau Djawa merupakan daerah yang paling maju di Asia[17]. Mereka membuat jalur kereta api yang lengkap tidak hanya untuk kenyamanan dari dua ratus ribu penduduk Belanda. Kesejahteraan masyarakat ditingkatkan setelah ada pengenalan kebijakan etika[18] yang dihimbau oleh Ratu Wilhelmina di awal abad 20. Meski sulit tapi akhirnya orang-orang Belanda memberikan kontribusinya untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah orang-orang asing yang kembali ke sana setelah kemerdekaan, semata-mata untuk kepentingan ekonomi tanpa memikirkan kemajuan negara dan kehidupan penduduknya. Seorang pengunjung seusia saya yang juga berasal dari Jepang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat oleh orang-orang Belanda merupakan “aristokrasi dari keyakinan yang baik” dengan pegawai-pegawai yang memenuhi syarat. (Tsurumi, Yusuke Nanyo Yuki (Travel around Nanyang), Dai-Nihon Yubenkai, Tokyo 1917). Cucu laki-laki penulis berpendapat bahwa Marquis Tokugawa bukan seorang anti kolonial dan ia menghargai sisi positif dari penjajah terutama orang-orang Belanda yang tidak lagi haus kekuasaan dunia dan berkonsentrasi pada modernisasi Hindia Timur.
Marquis Tokugawa lebih tertarik pada negerinya sendiri dibandingkan dengan bangsa atau negara lain, seperti halnya kehidupan, budaya dan sejarah dari orang-orang itu. Ia memuji kota Batavia (sekarang Djakarta) sebuah kota yang dibangun oleh orang-orang Belanda, sebagai “sebuah kota yang subur, dengan rumah yang bercat putih sehingga tampak indah dan serasi” dan ia juga berkomentar hal yang sama tentang kota lain. Ia gambarkan rumah-rumah beratap jerami dan berdinding anyaman bambu “serupa dengan sangkar serangga” tetapi nyaman dan tidak kotor[19]. Dalam perjalanannya ke pulau Djawa, Marquis Tokugawa sangat menikmati perjalanannya di atas kapal penumpang milik Belanda, dengan keramahtamahan para pekerjanya yang menyukai kebersihan. Ia berulang kali mengatakan bahwa, “mobilnya dapat berjalan diatas jalan-jalan yang mulus seperti sebuah anak panah” yang membuat pengunjung dari Eropa merasa iri. Sebagai ahli ilmu biologi yang telah mendapat banyak penghargaan dari laboratorium di Kebun Botani berpendapat bahwa fasilitas di sana sangat baik dan aku ingin bisa tinggal di sana sebentar, melakukan pekerjaanku dan bebas dari gangguan apapun. Pernah ia mengeluh sambil bercanda, tentang lokomotif berbahan bakar kayu dengan alasan lebih ekonomis, dan tempat tidur hotel yang tidak menyediakan selimut, dan lain lain.
Penulis menulis banyak tentang orang-orang pribumi, seperti halnya para jongos (kacung) di atas kapal penumpang, penjaga malam di hotel, penari wayang dan pemain musik tradisional yang ia amati dari jarak tertentu. Dengan penuh rasa terima kasih ia memberi koin pada anak-anak perempuan desa yang dengan gembira menawarkan bunga di tepi danau. Ia membeli perhiasan berbentuk kumbang yang terlihat mahal dari seorang anak laki-laki yang berpakaian lusuh. Ia melihat perselisihan antara seorang wanita tua dengan rekan kerjanya seperti komedi kemudian seorang polisi sebagai orang yang dihormati membantu menyelesaikannya. Ia tidak pernah memandang rendah mereka maupun membedakan ras apapun. Ia berkata, “ia tidak memperhatikan beberapa ras yang terlihat seperti ukiran kayu yang tak berekspresi, tidak seperti gadis-gadis soenda yang menarik perhatiannya ...”, itu adalah pujian bagi perempuan Sunda yang cantik.
Ketika mengunjungi Monumen Buda candi Boroboedoer, Marquis Tokugawa sangat mengagumi seni dan sejarahnya yang tak dikenal. Pada kenyataannya arsip dan dokumen tua sebelum kedatangan Islam sangat jarang ditemukan di pulau Djawa dan pulau di sekelilingnya[20]. Marco Polo yang mampir di Djawa Lesser (sekarang Sumatra) pada tahun 1292(?) dalam perjalanan pulang dari negeri Cina dan menulis secara rinci tentang Islamisasi dari kerajaan yang telah terbagi-bagi tidak menjangkau pulau Djawa. Dia hanya mencatat, itupun menurut desas-desus para pelaut, bahwa orang-orang di sana penyembah berhala yang dikuasai oleh seorang raja yang berkuasa di negeri yang kaya raya (Polo, Marco (diterjemahkan oleh R. E. Latham), The Travels, Penguin Classics, London 1958). Mengenai orang-orang yang beragama Buda, I-Ching, seorang imam bangsa Cina beragama Buda, mencatat diakhir abad ketujuh dalam buku ajaran Buda yaitu, “Seratus Satu Karma dari Muulasarvaastivaada, Jilid 5 (One Hundred and One Karmas of Muulasarvaastivaada,Vol.5, 根本説一切有部百一羯磨・巻五)” bahwa “Belajar sangat dipandang penting di ibukota Sriwijaya (di Sumatra) dan di sana ada seribu bonzes (biksu) berkeliling meminta sedekah. Tingkatan dari studi dan mutu dari bonzes adalah setara dengan di pertengahan India. Para bonzes Tang yang ingin membaca ajaran Buda direkomendasikan untuk tinggal di sana dalam satu atau dua tahun, sebelum mereka pergi menuju India.” (H. Wada, A History of Races in The South-East Asia (a text book for University of Air), 1987). Apakah keadaan seperti itu sama di Kyoto, Jepang, pada jaman dulu? Di mana kita dapat mempunyai gambaran baik dari banyak literatur dan lukisan. I-Ching menguraikan bahwa ajaran Buda adalah sama majunya atau lebih maju di pulau Djawa pada abad ke sembilan.
Pada peninggalan Kerajaan Hindu di halaman candi Prambanan, penulis mempertimbangkan “para guru yang tak dikenal, atau seniman besar pada waktu yang tak diketahui telah meninggalkan banyak karya-karya seni yang mengagumkan, terutama pagoda-pagodanya, dapat disejajarkan atau bahkan lebih baik dari karya seni terkenal di Eropa”. Di Monumen Buda Boroboedoer, ia terkesan oleh pendapat para peneliti bahwa, “Kehidupan orang-orang Djawa dilukiskan di sini lebih dari seribu tahun yang lalu dan tidak jauh berbeda dengan kehidupan saat ini.” Walaupun penganut Islam menjadi agama utama di pulau Djawa, tradisi dari agama terdahulu dan para penyembah benda mati tetap berlaku. Hal itu dapat dilihat bahwa orang-orang tetap menyukai cerita Mahabarata dan Ramayana, sangat berbeda situasinya dengan negara-negara Timur Dekat (Near-East) dan negara-negara yang bertetangga dengan Arabia. Hal itu tidak berubah meski setelah kedatangan bangsa Eropa. Marquis Tokugawa merasa simpatik pada pengunjung candi yang mencoba menyentuh patung Buda namun tak pernah berhasil menyentuhnya dengan harapan berbagai keinginan mereka dapat dikabulkan. Ia berhasil menyentuh patung Buda itu namun ia berkata, “Aku tidak yakin harapanku akan terkabulkan, sebab itu merupakan sesuatu yang sulit.”, meninggalkan sebuah pertanyaan bagi para pembaca apa kira-kira harapannya itu.
Kediaman Gubernur Jenderal yang megah di Batavia dan istana Soesoehoenan di Solo, mengingatkannya pada istana tua milik keluarganya di Nagoya yang telah diserahkan pada Kaisar setelah Restorasi Meiji (istana itu terbakar habis di suatu serangan udara tanggal 14 Mei 1945) tetapi ia tidak menyinggung tentang hal itu. Barangkali, ia mempunyai perasaan yang kuat tentang demokrasi, dan menaruh sudut pandangnya terhadap rakyat biasa, bahwa “demokrasi” diadopsi sebagai anonim dari aristokrasi.
Keingintahuannya tentang kultur orang-orang djawa akhirnya tercapai ketika ia melihat upacara tradisional angkatan perang Kesoeltanan di Jogjakarta. Menurutnya, upacara itu tidak sama dengan pawai. “Barangkali, anakronisme tidak perlu di pulau Djawa.” Pernyataan itu masih benar sampai sekarang, setelah lebih dari setengah abad, di Republik Indonesia, dan drama yang sama masih tetap dimainkan setiap tahun, seperti yang di-saksikan oleh penerjemah sendiri di beberapa tahun terakhir ini.
Sesungguhnya, seseorang boleh beranggapan bahwa kecintaan terhadap tradisi merupakan corak karakteristik dari orang-orang djawa atau orang-orang Indonesia. Selama tujuh dekade setelah kunjungan Marquis Tokugawa, mereka telah mengalami masa-masa paling sulit yang belum pernah terjadi dalam sejarah selama ribuan tahun, yaitu ketika mereka melihat penyerbuan oleh bangsa Jepang, perjuangan untuk kemerdekaan, konflik-konflik politik, dan berbagai kesulitan ekonomi yang meliputi seluruh bangsa Indonesia. Ekspansi ekonomi yang cepat sepanjang rejim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto telah menyebabkan “Yang kaya menjadi lebih kaya dan yang miskin menjadi lebih miskin...”, seperti syair lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi terkenal, Rhoma Irama, diantara populasi yang telah “menjerit karena himpitan ekonomi” sepanjang separuh abad, dan terus didorong ke arah krisis moneter yang baru-baru ini terjadi. Namun nampaknya, rangkaian peristiwa-peristiwa dan perubahan yang secara resultan dari struktur sosial tersebut tidak banyak mempengaruhi gaya hidup atau cara berpikir orang-orang Indonesia. Seperti yang dilihat para wisatawan saat ini sama dengan yang diuraikan oleh Marquis Tokugawa. Apakah hal itu merupakan kekuatan atau kelemahan orang-orang Indonesia, atau kedua-duanya?
Orang-orang Indonesia juga suka memelihara atau membangun kembali bangunan-bangunan tua. Seperti gedung pencakar langit berdiri berdampingan di area yang baru dikembangkan di Jakarta, saat itu kota Batavia dipelihara dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Termasuk juga rumah di daerah tua Weltevreden, mencakup tempat Kediaman Gubernur Jenderal juga dipelihara dan dimanfaatkan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah adanya perubahan nama-nama jalan dan bangunan. Mereka berusaha keras mengganti tiang kayu penopang atap bangunan dengan kayu yang melengkung, sebuah bangunan yang indah ciri khas abad ke 20. Bangunan tersebut dapat kita temukan di dalam aula Institut Teknologi Bandoeng tempat berlangsungnya Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik, atau stasiun kereta api di Pekalongan, Djawa Tengah. Kebun Botani Bogor, termasuk halaman pemakaman orang-orang Belanda di dalamnya selalu dijaga agar bersih dan rapi, walaupun laboratoriumnya sudah tidak lagi mengalami masa-masa kejayaan seperti di masa lalu. Prambanan sudah tidak terlihat seperti reruntuhan yang menyedihkan lagi, setelah dilakukan pemugaran sebagai hasil dari usaha mereka memecahkan batu-batu berukir tiga dimensi dan itu merupakan pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda. Sebagai tambahan, orang-orang gemar melestarikan warisan kebudayaan mereka seperti, tempat pembuatan bir warisan dari Heineken sampai sekarang masih digunakan oleh Bir Bintang. Gedung baru Museum Nasional, Jakarta, dengan bagian depan bergaya Parthenon mirip dengan bangunan Museum Nasional terdahulu yang merupakan bangunan tertua yang dibuat tahun 1868. Di dalam Gedung Sate di Bandoeng, sekarang digunakan sebagai Kantor Gubernur Djawa Barat, kita dapat melihat sebuah aula pertemuan yang baru disesuaikan dengan desain arsitektur aslinya pada tahun 1920. Gedung penelitian baru yang ditambahkan di Institut Teknologi Bandoeng mempunyai atap dan pilar-pilar batu yang sama seperti yang Marquis Tokugawa lihat. Gedung itu tampak modern dan multi-guna. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa negara telah banyak kehilangan rumah-rumah tua dan bahkan jalan diakhir dekade ini[21].
Tradisi orang-orang Indonesia seperti itu bukan ciri khas Asia tetapi sudah banyak dipengaruhi oleh bangsa Eropa yang terjadi selama empat ratus tahun, lepas dari mereka merasa bangga akan hal itu atau tidak. Di Singapoera tidak banyak meninggalkan kesan berarti yang dapat diingat oleh Marquis Tokugawa dalam bukunya. Di sebuah negara di Asia, bangunan tua bekas markas besar penjajah telah dirobohkan atas perintah presiden karena bangunan itu dipandang sebagai hal yang memalukan bagi bangsa mereka, lima puluh tahun setelah kemerdekaan mereka. Marquis Tokugawa sebagai orang yang telah menemukan persamaan kultur dan kehidupan antara orang djawa dan orang Jepang[22], berkomentar dengan cara yang berbeda, jika mereka melihat keadaan saat ini dimana Perang Dunia Kedua telah membinasakan tidak hanya sistem tetapi juga hati nurani yang dulu dimiliki orang-orang itu.
Mengenai Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat yang diadakan oleh orang-orang Belanda di Hindia Timur, para pembaca, juga ilmuwan khususnya, boleh berbagi pendapat yang sama dengan penerjemah bahwa kongres tersebut merupakan peristiwa dari “Peristiwa masa lalu yang indah” ketika aktivitas ilmiah dinilai secara mutlak, seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebagai rasa hormat terhadap tujuan kongres tersebut, dan para ilmuwan menerima rasa hormat yang penuh dari pemegang kekuasaan dari berbagai negara, dan diijinkan menjadi mandiri dari masyarakat lainnya. Sesungguhnya, penulis berulang-kali menyebut para rekan kerjanya dan dirinya sendiri sebagai “ilmuwan yang handal” dan menyinggung “orang-orang seperti itu (yang disebut ilmuwan), memiliki bidang penelitiannya sendiri-sendiri, tidak mencampuri urusan orang lain”. Ia juga mengutip kata-kata rekan kerjanya, “Pemerintah Belanda sangat dermawan” untuk menjamu hampir tiga ratus tamu dalam periode satu bulan. Barangkali, para peserta kongres sebelumnya di Australia dan Jepang, juga para peserta di kongres berikutnya di Kanada dan Perancis Indo-Cina, pasti telah menerima keramahtamahan yang sama dari pemerintah negara masing-masing.
Para ilmuwan pilihan itu bukan hanya handal tetapi mereka juga orang-orang yang mulia “yang siap dan berkeinginan untuk mendiskusikan dan memecahkan permasalahan, kedudukan menjauhkan diri dari politik dan membebaskan diri dari chouvinisme nasional dan kurang lebih untuk kepentingan pribadi.” Seperti halnya Dr. de Graeff, Gubernur Jenderal Hindia Timur, ikut hadir dalam acara pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat. Ketika Singapoera jatuh ke tangan angkatan perang Bangsa Jepang pada Februari 1942, seorang vulkanolog dan geolog bernama Prof. Tanakadate serta anggota tetap Kongres, langsung pergi ke sana tanpa perintah resmi dari Saigon tempat di mana ia sedang berkunjung untuk suatu misi yang berbeda. Di Museum Raffles, di Perpustakaan Kebun Botani, ia menjabat sebagai direktur, dengan Dr. Holttum sebagai wakil dan Dr. Corner sebagai sekretarisnya. Di masa-masa awal kepemimpinannya mereka memainkan suatu peran yang rumit untuk melindungi institusi dan pegawai-pegawai berkebangsaan Inggris. Pada bulan September 1942 ia membujuk dan menyerahkan jabatannya kepada Marquis Tokugawa yang baru tiba dari Tokyo pada bulan Maret[23]. (Tanakadate Hidezo Achievements Publishing Group, Tanakadate Hidezo - Achievements and Memoirs, Sekai-Bunko, Tokyo 1975).
Mereka memperbaharui buku-buku yang mereka temukan di rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya dan meletakkannya di perpustakaan sebagai koleksi. Ketika Prof. Tanakadate dan Marquis Tokugawa mendengar tentang pekerjaan yang tak diterbitkan oleh seorang ahli botani, mereka dengan seketika mencetak naskah itu, dengan biaya sendiri di Kuala Lumpur, di mana fasilitas pencetakan yang selamat dari bom. Mereka tidak mengkawatirkan akan penggunaan bahasa Inggris, karena bahasa Jepang dilarang pada jaman itu. Prof. Koriba, pensiunan dari universitas Kyoto, yang juga anggota kongres, datang dan mengambil alih tanggung jawab itu, sampai akhirnya ia kembali ke Britain pada bulan September 1945. Ilmuwan merupakan warganegara dunia dan tidak ada musuh di antara mereka. Sebagian dari cerita ini telah dimasukkan ke dalam buku The Marquis : A Tale of Shonan-to, ditulis oleh Prof. E. J. H. Corners dan diterbitkan oleh Heinemann Books (Asia) Ltd. pada tahun 1981.
Kontribusi yang diberikan para ilmuwan Jepang adalah untuk melindungi ilmu pengetahuan yang merupakan bagian penting di Asia. Prof. Hatai, delegasi dari Jepang yang juga ketua Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik yang keempat, pergi ke negara Filipina untuk menjadi direktur lembaga Ilmu Pengetahuan (Bureau of Science), di Manila. Di Djawa dan Sumatra, yang meliputi semua institusi penelitian di Batavia, Bandoeng, Buitenzorg, Medan dan tempat lain telah dilindungi. Pada bulan Maret-April tahun 1942, Prof. Tanakadate, meminta Marquis Tokugawa pergi ke sana setelah menyerah dari Belanda dan memerintahkan Belanda untuk kembali ke posisi mereka (Tanakadate, Hidezo, The Seizure of Southern Cultural Institutions, Jidai-sha, Tokyo 1944). Kebanyakan orang memilih Prof. T. Nakai dari Universitas Tokyo sebagai Direktur Kebun Botani Buitenzorg dan Prof. R. Kanehira dari Universitas Kyushu, yang bertindak sebagai Kepala Herbarium, mereka berinisiatif dan berusaha keras untuk melindungi Kebun dari angkatan perang Jepang yang ingin memotong dan menggunakan pohon untuk balok kayu. (Levelink J., Mawdsley A. and Rijnberg T., Four Guided Walks: Bogor Botanic Garden, Bogorindo Botanics, Bogor 1996).
Itu merupakan aktivitas para ilmuwan Jepang pada waktu itu di Asia yang dikoordinir oleh Marquis Tokugawa. Berlawanan dengan mereka para penulis dan seniman yang direkrut sebagai staf propaganda dan mengorganisir untuk membenarkan aturan Jepang[24].
“Journeys to Djakatra” telah lama tidak diterbitkan dan jarang dibaca di Jepang, sebab wisatawan lebih memilih buku petunjuk untuk mendapatkan “cara” mudah mencari informasi dengan cepat. Ilmu pengetahuan adalah salah satu cara lain. Penerjemah percaya bahwa buku ini tetap bermanfaat sebagai buku petunjuk untuk pulau Djawa, seperti juga penulis berharap pekerjaannya di masa lalu bukanlah “sesuatu yang salah”.
[1] Ieyasu Tokugawa (1542-1616) adalah seorang pemimpin prajurit sepanjang “Jaman Pertempuran” dari Jepang pada abad keenambelas. Ia memenangkan peperangan di akhir tahun 1600 dan pada tahun 1603 mendirikan pemerintahan Shogun di Yedo (sekarang Tokyo). Pemerintahan ini bertahan sampai akhirnya pemerintah mengembalikannya kepada Kaisar pada Restorasi Meiji pada tahun 1868. Ieyasu menciptakan tiga cabang keluarga, Nagoya (Owari), Wakayama (Kishã) dan Mito (Hitachi). Tokugawa berasal dari keluarga Matsudaira, merupakan garis keturunan Genji yang berasal dari Kaisar Seiwa (pemerintahan 858-876) dan sangat berkuasa di abad keduabelas sampai abad ketigabelas. Kemudian, garis keturunan ayahnya berhubungan dengan Tokugawa. Ayahnya, Pangeran Yoshinaga Matsudaira dari Echizen (1828-90) merupakan orang yang berperan penting diakhir pemerintahan Shogun dan menjabat sebagai Menteri Keuangan di pemerintah Meiji yang baru.
[2] Yayasan Tokugawa Reimeikai didirikan pada tahun 1931. Museum Seni Tokugawa adalah salah satu museum seni rupa terbaik di Jepang dimana dokumen dan harta benda keseluruhannya dikumpulkan dan dipilih oleh keluarga Owari-Tokugawa selama tiga ratus tahun. Penelitian terhadap koleksi-koleksinya terus berlanjut sampai sekarang. Institut Sejarah Ilmu Kehutanan Tokugawa (The Tokugawa Institute for the History of Forestry) merupakan salah satu dari beberapa institusi penelitian pribadi dan menerbitkan buletin sendiri. Institut Penelitian Biologi Tokugawa (The Tokugawa Institute for Biological Research) ditutup pada tahun 1970.
[3] Dalam buku “Ketika berboeroe di Hoetan Malaya” (Hunting in the Jungle of Malaya), Yoshichika menulis ketika menerima surat dari istrinya di Singapoera,
“Beberapa foto hilang ketika aku membuka amplop. Itu adalah gambar yang aku ambil di laboratorium dan beberapa tidak dapat dicetak karena keterbatasan waktu. Ada beberapa noda di sana akibat kegagalan pengambilan gambar tetapi gambar terlanjur direkam. Bila melihat foto ini, aku merasa diriku terkunci di laboratorium dan mengamati mikroskop, dan diriku yang bersiap melawan harimau dan gajah yang berbahaya tanpa menghiraukan panas di daerah yang beriklim panas seperti dua orang yang berbeda yang tinggal di dunia yang berbeda, dan bingung mana yang nyata. Itu merupakan diriku dengan dua karakter berbeda”.
[4] Banyak orang Jepang pindah ke luar negeri setelah Restorasi Meiji. Kebanyakan yang menuju Hawaii, California dan Brazil adalah kelompok petani dari desa yang miskin, dan yang pindah ke Asia Tenggara adalah orang yang merdeka. Ada juga para pedagang tetapi kebanyakan mereka bekerja sebagai juru masak dan buruh. Banyak wanita melakukan bisnis dimalam hari. Marquis Tokugawa menulis dalam “Ketika Berboeroe di Hoetan Malaya” (On Hunting in the Jungle of Malaya) :
“Wanita-wanita Jepang sangat terkenal di Jalan Malaya, Singapoera. Sangat ironis bahwa orang-orang Jepang menghilang dari Nanyo setelah Konsul Jepang melarang bisnis mereka tahun 1918, lalu mereka dibuang selama tiga tahun. Alasannya bahwa hal itu dipandang buruk dan memalukan bagi bangsa itu. Cepat atau lambat, orang-orang Jepang akan kehilangan aktivitasnya di Nanyo sepenuhnya”.
Meskipun demikian, sekitar tahun 1940 populasi orang Jepang sebanyak 7.000 orang dan 51 komunitas orang Jepang ada di pulau Djawa, sebagai penanaman modal (Ishii, Yoneo (ed.) Encyclopaedia of Indonesia, Doho-Sha Publ. Tokyo 1991). Mereka berhubungan dengan pemerintah setempat menjelang dimulainya Perang Dunia Kedua, dan kehilangan kebebasan berpendapatnya, seperti yang dicemaskan oleh Marquis Tokugawa.
[5] Jumlah penduduk Jepang di Asia Tenggara diperkirakan lebih dari lima ribu orang, sebelum Jepang menutup kesempatan bagi orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke negara-negara lain maupun yang ingin kembali ke Jepang. Peraturan itu telah diberlakukan diakhir tahun 1639 oleh Shçgun yang ketiga. Di antara tentara sewaan, yang paling terkenal adalah Nagamasa Yamada bersama-sama orang kepercayaannya, dengan seorang pengawal Raja dari Ayuthia. Pada tahun 1620 VOC merekrut lebih dari tiga ratus orang Jepang dan mengirim mereka ke Batavia dan daerah lain yang merupakan bagian dari Hindia Timur. Para laki-laki merupakan pedagang dan prajurit (samurai) sedangkan yang perempuan adalah sukarelawan untuk dijadikan pasangan orang Belanda. Para prajurit bertugas mengambil alih Djakarta dari Persekutuan Bantam-Inggris pada tahun 1619. Pada tahun 1623 pasukan Inggris yang menguasai Ambon telah dikalahkan oleh orang-orang Belanda dan terdapat sembilan orang prajurit Jepang. (From Wada M., Modern History of South-East Asia (a text book for University of Air, 1991 dan referensi lain)
[6] Berbeda dengan buku Tokugawa “Journeys to Djakarta”, “Nangokuki (Travels around the Southern Countries), Niyu-Sha, Tokyo 1910”, ditulis oleh Yosaburo Takekoshi, dan “Nanyo Yuki (Travels around Nanyang), Dai-Nihon Yubenkai, Tokyo 1917” ditulis oleh Yusuke Tsurumi, menulis dari sudut pandang kebangsaan. Dua buku ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan yang disebut ”Nanshinron” (Teori ke arah Selatan), walaupun para penulisnya tidak bermaksud untuk menjadi sumber inspirasi seperti aktivitas-aktivitas militer yang benar-benar menjadi kenyataan pada tiga dekade kemudian. Bahwa beberapa negara lain juga memiliki minat yang besar di Hindia Timur telah menjadi kenyataan, seperti ditulis dalam buku Carpenter (Java and the East Indies, Doubleday, Page & Scott Co., Garden City-New York 1926) yaitu, “Bandong, yang aku tulis ini, akan menjadi suatu tempat peristirahatan yang populer bila Amerika menguasai pulau Djawa.”
[7] Karangan, “Perboeroean di Malaya” (Game in Malaya), tidak termasuk dalam terjemahan ini ditulis dalam tulisan Jepang.
[8] Marquis Tokugawa telah membalas kunjungan kehormatannya kepada Soeltan di Jogjakarta dan Soesoehoenan di Solo yang merupakan sedikit pengecualian untuk warganegara Jepang. Sepanjang periode sebelum perang kantor kolonial Belanda, sangat berhati-hati terhadap orang Jepang yang mengadakan kerjasama dengan para penguasa pribumi, khawatir akan mengikis kekuasaan mereka. Yosaburo Takekoshi, seorang negarawan dan juga penulis, serta Yusuke Tsurumi, seorang pegawai tinggi dari Kementerian Perhubungan, tidak ikut dalam kedua acara tersebut, mungkin karena ”Soeltan sibuk menyiapkan pernikahan putrinya” dan karena ”surat dari Gubernur Jenderal hanya tiba pada hari keberangkatannya dari Solo”. (Yosaburo Takekoshi, Nangokuki (Perjalanan berkeliling Negara-Negara Selatan/Travels around the Southern Countries), Niyu-sha, Tokyo 1910; Yusuke Tsurumi, Nanyo Yuki (Perjalanan berkeliling Nanyang/Travels around Nanyang), Dai-Nihon Yubenkai, Tokyo 1917). Oleh karena itu mereka mengatur sebaik mungkin kunjungan kehormatan Marquis Tokugawa agar berjalan lancar. Atau mungkin karena ia bukan seorang politikus atau pejabat tetapi seorang akademis, yang mempunyai kedudukan di Kerajaan dan otomatis dipandang sebagai orang terhormat.
[9] Secara umum dikatakan bahwa orang-orang Belanda dihormati penduduk pribumi bagai “setengah kekanak-kanakan” dan ingin membiarkan mereka seperti itu. Kesulitan Pemerintah Batavia adalah mengubah kebijakan awal dan memperkenalkan pendidikan yang modern. Setelah akhir abad ke sembilan belas mereka berusaha mengatasi kurikulum yang berorientasi keagamaan pada sekolah Islam yang disebut pesantren. Kesulitan lain adalah kondisi bangunan sekolah yang tidak dapat menampung peningkatan populasi yang membumbung tinggi sekitar 1.8 kali lipat selama 25 tahun (Abdullah, Taufik ed. (Terjemahan dalam bahasa Jepang oleh. Shiraishi, T. Shiraishi), Islam di Indonesia, Mekon, Tokyo 1985). Konon tidak banyak orang tua dari siswa kelas tertinggi menganggap perlu jenjang pendidikan selanjutnya dan mengirimkan anak-anak mereka ke universitas dan perguruan tinggi.
[10] Technische Hoogeschool te Bandoeng (berdiri tahun 1920), Rechten Hoogeschool Batavia (berdiri tahun 1924) dan Medische Hoogeschool Batavia (berdiri tahun 1927). Data-data terakhir menyebutkan bahwa rencana pembangunan sekolah-sekolah tersebut sudah ada sejak tahun 1852. Persetujuan atas rencana pengembangan Universitas Batavia, maka dibentuk Sekolah Sastra di Batavia tahun 1940 dan Sekolah Pertanian tahun 1941 di Buitenzorg.
[11] Sebagai contoh, Partai Komunis Indonesia dideklarasikan tahun 1920 dan terjadi pemberontakan pada tahun 1926, Partai Nasional Indonesia dibentuk tahun 1927, Soekarno dipenjara tahun 1929, tahun 1928 Sumpah Pemuda dikumandangkan untuk melukiskan “Indonesia” sebagai nama negara, bangsa dan bahasa, dan masih banyak lagi.
[12] Angkatan perang Jepang ditempatkan di Pelabuhan Arthur setelah pengambilalihan dari Rusia pada tahun 1919 menjadi unit militer yang semi-independen, yang disebut Kanto-Gun, dan diperluas ke Manchuria untuk melindungi Jalur kereta api Manchuria. Pada tanggal 7 Juli 1932, terjadi perang melawan Cina dipicu oleh Peristiwa di Jembatan Marco Polo. Didalam Negeri, militer berkuasa dan Lembaga Hukum dibentuk pada tahun 1925 untuk mengendalikan dan membersihkan tidak hanya komunis tetapi juga warganegara yang beraliran liberal.
[13] Frank G. Carpenter menulis dalam “Jawa dan Hindia Timur (Java and the East Indies) ”, Doubleday, Page & Scott Co., Garden City-New York 1926:
“Orang berkulit coklat dari pulau Djawa adalah orang yang paling ramah dari semua bangsa berwarna selain Jepang.”“Aku telah bepergian hampir di seluruh pulau Djawa, dan aku bertemu dengan penduduk pribumi yang sedang kelaparan. Negeri ini memberi makan dirinya sendiri, dan mengeluarkan berjuta-juta dolar untuk produknya setiap tahun...’,
“Para Pejabat diperlakukan seperti halnya orang Eropa dan isteri kepala desa mempunyai kedudukan yang sama seperti isteri Kepala daerah. Kepala daerah dan Bupati duduk bersama-sama pada saat makan malam , dan sepertinya sederajat....?, dan lain lain.
[14] John C. van Dyke menulis ”Pulau Jawa dan Pulau-pulau Sekitar Belanda Hindia Timur (In Java and the Neighboring Islands of the Dutch East Indies)”, Charles Scribner Sons, New York dan London 1929:
“ Sulit untuk menemukan kesalahan administrasi orang-orang Belanda di pulau Djawa dan pulau-pulau lain. Kenyataannya bahwa Belanda Hindia Timur telah diatur dengan baik, lebih baik dibandingkan dengan jajahan negara manapun. Administrasi orang Amerika memiliki kesamaan dengan orang-orang Belanda dalam hal efisiensi, tetapi berlanjut dengan kerugian keuangan. Orang-orang Belanda secara tidak langsung menjadi kaya di pulau Djawa, tetapi mereka juga membuat penduduk pribumi mendapatkan uang. Lebih dari itu, mereka juga mengembangkan negara. Mereka berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan seimbang dan jajahan yang makmur. Untuk itu mereka mencoba menetapkan hak atas tanah para penduduk pribumi, memperkenalkan metode irigasi dan pertanian, peduli akan hutan, mendirikan universitas dan sekolah, membangun kota, jalan dan jembatan, membuka rute transportasi baru, dan melakukan seribu satu hal untuk perbaikan kota dan negeri. Hasilnya adalah para penduduk berkecukupan pangan, perumahan, dan pakaian, terlihat bahagia dan tampak senang. Pulau Djawa menjadi tempat yang menyenangkan bagi para pelancong, paling menyenangkan dari semua negara-negara tropis. Orang-orang Belanda harus menerima penghargaan untuk ini. Mengapa tidak dikatakan tanpa syarat?”.
[15] Menurut Undang-undang, pada tahun 1922 Hindia Timur seperti halnya Suriname dan Curacao memperoleh status yang sama sebagai bangsa Belanda. Itu sungguh berbeda dari beberapa Wilayah Asia lain seperti, India Britania dan Filipina Spanyol/Filipina Amerika. Dan tidak ada alasan bagi Gubernur Jenderal Hindia Timur, Mr. A. W. L. Tjarda Starkenborgh Van Stachouwer yang berniat pada tahun 1941, ketika Belanda diduduki oleh Jerman, untuk memindahkan Ratu Wilhelmina dan pemerintahannya dipengasingan di London ke Batavia, tanpa mengantisipasi pendudukan Jepang satu tahun kemudian. (Gagasan ini tidaklah disetujui oleh Winston Churchill maupun Ratunya.)
[16] Mayoritas orang-orang Belanda di Hindia Timur adalah sebagai penduduk tetap di sana, sedangkan banyak kolonialis seperti, orang-orang Inggris di India, cenderung kembali ke negaranya setelah mereka pensiun. Sebelum akhir abad ke sembilan belas penduduk pasangan orang Belanda yang memiliki keturunan berkulit putih jumlahnya terbatas, karena pasangan wanitanya kesulitan melakukan perjalanan laut yang sangat jauh. Oleh sebab itu, banyak orang Belanda menemukan pasangan dari penduduk pribumi, seperti wanita Ambon dan Bugis yang telah memeluk agama Kristen di jaman penjajahan Portugis, atau wanita berdarah campuran (Eropa dan Indo). Dahulu kala, sebelum Jepang menutup diri dari negeri lain di awal abad ke-17, orang-orang Belanda mengajak wanita-wanita Jepang menjadi pasangan mereka karena lebih beradab, dan agama mereka yaitu Buda, lebih bersikap toleran terhadap perkawinan campuran dibandingkan Islam. (Boxer, C. R., Kerajaan Orang-orang Belanda/The Dutch Seaborne Empire 1600-1800, Penguin Books-Hutchinson, London 1990, dan acuan yang lain).
[17] Konstruksi perkotaan di Batavia dan kota lainnya seperti halnya sistem jalan di seluruh negeri dimulai antara tahun 1808 sampai 1811 oleh Marshal H. W. Daendels yang diutus sebagai Gubernur Jenderal Belanda di bawah pengawasan Perancis. Pada tahun 1816 Hindia Timur dikembalikan kepada Belanda dari tangan Inggris, dalam persetujuan Perdamaian Vienna di tahun sebelumnya, modernisasi pulau Djawa menjadi lebih cepat. Pada tahun 1858 sistem telekomunikasi pertama diperkenalkan, kapal selam kabel diluncurkan tahun 1859, jasa pos dimulai tahun 1862, kereta api untuk umum dibuka tahun 1867, pelabuhan modern di Tanjung Priok Batavia mulai dibangun tahun 1870 , mesin ketik diperkenalkan ke seluruh kantor pemerintahan tahun 1900 , dan seterusnya, hanya 10-15 tahun setelah itu semua diperkenalkan di Belanda. (Torchiana, H. A. van Coenen, Tropical Holland, An Essay on the Birth, Growth and Development of Popular Government in an Oriental Possession, University of Chicago Press., Chicago 1921, Shiraishi, Takashi, Brochure of “Pramoedya Series 2: The Earth of People 1", Mekon, Tokyo 1986, dan acuan yang lain).
[18] Berbagai tindakan dilakukan dengan cepat untuk memindahkan jabatan Gubernur Hindia Timur dari Den Haag ke Batavia dan ke penguasa lokal. Pendidikan untuk orang orang pribumi, seperti sekolah dasar dan sekolah lanjutan mulai dibuka dan tiga bagian pendidikan direncanakan pada tahun 1920. Volksraad dilantik pada tahun 1918. Sementara kebijakan membuat pejabat yang berpendidikan terlibat dalam urusan administrasi, sehingga memicu pergerakan anti-kolonial.
[19] J. W. B. Money menulis dalam bukunya, “Pulau Jawa atau Bagaimana Mengatur Daerah Jajahan (Java or How to Manage a Colony)” pada tahun 1861 pemerintah Hindia Timur memperkenalkan suatu hukum untuk membersihkan dan memperbaiki rumah dua kali dalam satu tahun, tidak hanya untuk bangsa Eropa, dan penduduk pribumi diajarkan bagaimana cara hidup di lingkungan yang bersih.
[20] Sayangnya, kedatangan Islam di pulau Djawa sudah ada sejak jaman Khalifah Abbassiyyah (750-1258) saat umat Muslim sangat menghormati kebijakan yang berasal dari Yunani, India, atau Cina. Selain itu, orang-orang Arab yang datang ke pulau Djawa adalah para pedagang yang kurang berminat pada kultur dan seni, dengan asumsi bahwa kuil, biara, buku dan dokumen lama tentang ajaran-ajaran agama di pulau Djawa telah dilalaikan, jika tidak dengan sengaja dibinasakan, selama dan setelah penaklukan Islam (Abad ke 15-16).
[21] Sebagai contoh Gedung Masyarakat Harmonie yang dibangun oleh kontraktor pribumi pada tahun 1815; dirobohkan pada bulan April 1985 atas perintah Lembaga Sekertaris yang tidak mengetahui nilai sejarahnya. Hal itu dilakukan hanya untuk memperluas jalan dan menyediakan areal parkir (Heuken, SJ Adolf, Histrical Sites of Jakarta, 6th Ed., Cipta Loka Caraka Fundation, Jakarta 2000). Bangunan hotel-hotel tua yang bergengsi seperti Hotel des Indes, Hotel der Nederlanden dan Hotel Koningsplein sudah tidak ada lagi. Di Bandung, Jalan Dago (secara formal, Jalan Ir. H. Juanda) dan Jalan Cihampelas, salah satu jalan yang indah dengan rumah-rumah nyaman dan teduh, pohon-pohon rindang, sudah berubah total menjadi pusat perbelanjaan yang ramai sepanjang 15 tahun terakhir. Dan Jalan Pasteur diubah untuk membangun jembatan layang.
[22] Contoh yang sejenis adalah pengamatan Scidmore’s:
“ Orang-orang Djawa merupakan bunga terbaik dari bangsa Melayu - orang-orang memiliki peradaban, seni, dan literatur pada periode keemasan sebelum ditaklukkan pengikut Muhammad dan bangsa Eropa.... Mereka mempunyai suara yang lembut, tata krama yang lembut, air muka yang ekspresif dan bagus. Orang-orang di Asia selain Jepang memiliki daya tarik dan atraksi untuk mahluk asing.... Bahasa mereka terdengar lembut dan berirama seperti musik “Italia dalam iklim tropis”. Gagasan mereka sangat puitis; dan mereka cinta pada bunga dan parfum, musik dan tari, permainan yang gagah berani dan sikap emosional tehadap seni, membuktikan bahwa mereka membawa estetika sebagai kemenakan yang jauh, dimana ada campuran melayu yang sangat besar. Seperti halnya di Jepang, mereka sangat menghormati pangkat dan usia, dengan etiket dan kehormatan yang rumit juga ketelitian satu dengan yang lain;... (Scidmore, E. R., Java - The Garden of the East (pertama diterbitkan di New York pada tahun 1899), Oxford University Press Pte, Singapura 1984)”
[23] Di bawah judul, “Menerima Direktur Baru”, Prof. Tanakadate menulis:
Pemeliharaan bukanlah pekerjaanku. Pemikiran bahwa bila seseorang yang diragukan datang untuk menjadi direktur, dan Museum serta Perpustakaan diserahkan ke Pandemonium Shonan (Singapura), maka usahaku dimasa lalu untuk memugar dan mengembangkan institusi ini (sejak kejatuhan Singapura) akan menjadi sia-sia. Maka dari itulah aku meminta Marquis Tokugawa untuk datang setiap hari sebagai penasehat.
Bagaimanapun tidak ada ruang yang pantas untuk Marquis, aku menamai kantor direktur terdahulu untuk kantor direktur yang baru, “Ruang Marquis” dan melengkapinya dengan mebel terindah yang ada di Museum dan Perpustakaan. Kemudian, aku mempekerjakan dua wanita cantik yang segera tiba dari Jepang sebagai sekretaris sekaligus staf Perpustakaan. Mereka disediakan meja untuk menulis yang ditempatkan di depan ruangan Marquis. Kantor disiapkan itu menerima kehadiran Walikota, Tuan Oodachi, yang saat itu sedang berkunjung. Beliau menyatakan kantor itu sebagai kantor yang paling nyaman di kota itu. Setelah ruangan itu dilengkapi buku-buku yang disukainya, di awal bulan Agustus Marquis mulai nampak di kantor satu atau dua kali dalam seminggu dan berkata, “Aku kemari untuk belajar”. Sampai akhirnya pada tanggal 28 Agustus, ia berkata “Aku akan menjabat sebagai Direktur Museum dan Kebun Botani”.
Di Jepang, Tokugawa memimpin sebuah museum seni dan juga memiliki institut penelitian biologi yang dibangun sendiri. Karena itu, tidak ada yang mempertanyakan kemampuannya, tetapi orang lain yang telah menolak proposalku, berkata, “tidaklah pantas untuk mempertanyakan Marquis Tokugawa, seorang yang mendapatkan Urutan Ketiga Penerus Kerajaan*, dan pernah menjadi Penasehat tertinggi Administrasi Militer Malaya, bisa mendapatkan posisi sebagai direktur museum.” Tapi sekarang, bagaimanapun juga, harapanku telah tercapai. Itu merupakan prestasi terbesar yang dimiliki Marquis Tokugawa yaitu sebagai direktur baru Museum dan Perpustakaan yang sudah aku anggap seperti anakku. Dengan Tokugawa sebagai direktur, status dan otoritas institusi penelitian di wilayah baru semakin meningkat. Direktur baru memperkenalkan dirinya setiap pagi hari mulai dari tanggal 1 September, tetapi aku tetap mempunyai tanggung jawab administratif sampai penggantinya datang.
*Diterjemahkan untuk menggambarkan bangsa Jepang seperti yang ditulis oleh Prof. Tanakadate sebagai “Juunii Kun San-Tou” tetapi hal itu merupakan suatu kekeliruan. Yang sesungguhnya adalah pada bulan Mei 1924 Marquis menerima Gelar Bangsawan Ketiga yaitu urutan “Shou shii”. Sebelum tahun 1941 ia telah mencapai urutan “Juunii” yaitu Gelar Bangsawan Kedua satu tingkat diatas Gelar Bangsawan Ketiga.
[24] Penerjemah memberikan komentarnya pada buku, “Pulau Api- Suatu Tempat di Pulau Jawa dan Bali (The Islands of Fire - An Account on Java and Bali) terbit pada pada tahun 1944 ditulis oleh Tomoji Abe, dan mempertanyakan bagaimana seorang penulis besar dan sarjana literatur Inggris bisa mengkritik orang yang dijajah dengan nada yang kotor. Walaupun ia membenarkan aturan Jepang, setelah mencapai pulau Djawa menggunakan kapal militer lalu menenggelamkannya dalam Pertempuran Batavia pada tanggal 28 Februari 1942. Secara pribadi, Abe nampak mempunyai hubungan dengan orang-orang Belanda di luar pekerjaannya dan menulis sebuah novel setelah peperangan berjudul “Bunga Kematian” (Flowers of Death) pada tahun 1946, tentang nasib orang-orang Belanda. Seorang penulis lain yang berangkat bersama-sama dengan Abe, membuat karangan dan menyatukannya dalam buku yang berjudul, “Musim hujan telah datang” (The rainy season has come) pada tahun 1943. Karangan tersebut sangat objektif dan hampir tidak ada kritik atau komentar pada aturan orang-orang Belanda dan pendudukan Jepang.
Banyak penulis dan seniman menikmati keberadaan mereka di area yang diduduki Jepang dengan gaya hidup mereka. (Kamiya, T. dan Kimura. K. (ed.) Writers Conscripted to the Southern Area - the War and Literature, Sekai-Shiso-Sha, Tokyo 1996).